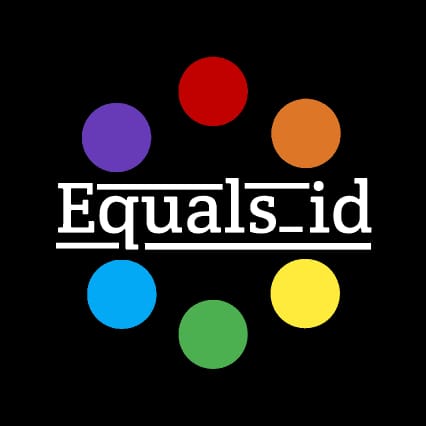Pemangku Kebijakan Tidak Benar-Benar Paham Yang Dirasakan ODHIV: Wacana Mengurangi Stigma Justru Memperburuk Stigma
Terakhir diedit : 29 Desember 2024
Estimasi waktu baca artikel sampai selesai menit
#StigmaDiskriminasi #faith2endaids #edukasiHIV #ODHIV #equals_id #UequalsU #UequalsU #letcommunitieslead #edukasiHIV #pencegahanHIV #LivingWithHIV #HopeForHIV #HidupDenganHIV #BreakingStigma #KualitasHidup #KesehatanMental
Stigma dan diskriminasi terhadap Orang dengan HIV dan AIDS masih menjadi tantangan signifikan dalam upaya penanggulangan HIV di Indonesia. Ironisnya, beberapa kebijakan yang dirancang untuk mengatasi masalah ini justru memperparah stigma yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa pemangku kebijakan mungkin belum sepenuhnya memahami pengalaman dan kebutuhan ODHIV.
Kebijakan yang Memperburuk Stigma
Beberapa peraturan daerah (Perda) yang bertujuan mencegah penyebaran HIV malah bersifat diskriminatif terhadap kelompok rentan dan minoritas seksual, sehingga menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan. Maraknya Perda diskriminatif dengan dalih mencegah penyebaran HIV membuat kelompok rentan dan minoritas seksual terhambat dalam mengakses layanan kesehatan termasuk akses pencegahan infeksi menular seksual ataupun HIV itu sendiri. Distribusi kondom bagi komunitas yang memang membutuhkan terhadang berbagai aturan Perda yang bahkan berpijak pada kebijakan Kementrian Kesehatan RI. Akses PrEP hingga saat ini belum dikampanyekan ketersediaannya secara terbuka sehingga banyak anggota komunitas rentan yang tidak mengetahui bagaimana akses PrEP. Doxy-PEP yang cukup efektif mencegah IMS karena bakteri juga dianggap sebagai suatu kampanye negatif, bersama dengan kampanye PrEP dan kondom yang dianggap dapat mendorong perilaku seks bebas. Upaya pengurangan stigma terhadap komunitas yang hidup dengan HIV melalui kampante TDTM (Tidak terDeteksi = Tidak Menularkan) tidak pernah terdengar gaungnya secara terbuka.
Padahal pencegahan penularan HIV melalui TDTM (Undetectable = Untransmittable) ini sangatlah efektif, dan sudah diendorse oleh WHO serta banyak lembaga kesehatan dunia lainnya.
Kondom yang dianggap sebagai upaya pencegahan IMS termudah dan termurah justru hanya boleh diedarkan untuk pasangan yang sudah menikah. Bahkan pada pasangan menikah usia muda, mereka disarankan akses kondom agar tidak mengalami kehamilan diusia sekolah. Allih-alih melarang dan membatasi pernikahan dini, negara seolah mentutup mata dan mendukung dengan akses kondom. Sementara remaja usia produktif dan matang reproduksi lain dipersulit akses kondom, begitu pula komunitas rentan yang secara usia sudah dewasa tetap mendapatkan kesulitan akses kondom.
Pengkaitan HIV dengan issue moralitas (dan seks bebas) juga menjadi penghalang orang-orang dari komunitas rentan untuk melakukan tes HIV dan pemeriksaan infeksi menular seksual lainnya.
Perbandingan dengan Negara Lain
Di negara-negara seperti Belanda dan Swedia (atau negara lain yang sudah berhasil mencapapai target glkobal 95:95:95), pendekatan terhadap kebijakan HIV lebih menekankan pada inklusifitas dan pengurangan stigma melalui edukasi masyarakat dan kebijakan yang mendukung hak asasi manusia. Sebaliknya, di Indonesia, stigma dan diskriminasi masih menjadi hambatan utama dalam penanggulangan HIV. Stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV dan populasi kunci telah diidentifikasi sebagai hambatan utama untuk respons yang efektif terhadap HIV.
Negara-negara tersebut telah menerapkan pendekatan berbasis bukti dalam penanganan HIV, termasuk penggunaan profilaksis pra-pajanan (PrEP) dan edukasi komprehensif yang berhasil menurunkan tingkat infeksi baru. Sementara itu, di Indonesia, stigma dan diskriminasi masih menjadi hambatan dalam implementasi strategi serupa.
Saran untuk Pemangku Kebijakan
1. Libatkan ODHIV dalam Perumusan Kebijakan: Dengan melibatkan ODHIV, kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan mereka dan mengurangi risiko diskriminasi.
2. Edukasi Publik secara Komprehensif: Kampanye yang meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HIV/AIDS dapat mengurangi stigma dan diskriminasi.
3. Revisi Kebijakan Diskriminatif: Tinjau ulang dan revisi peraturan yang berpotensi mendiskriminasi ODHIV untuk memastikan kesetaraan akses layanan kesehatan.
4. Pelatihan bagi Tenaga Kesehatan: Tingkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam menangani ODHIV tanpa prasangka, sehingga layanan yang diberikan lebih inklusif.
Statistik yang Mendukung
Data menunjukkan bahwa 53% ODHIV tidak mengetahui adanya perlindungan hukum atas hak mereka, membuat banyak dari mereka enggan mengakses layanan kesehatan karena takut diskriminasi.
Kesimpulan
Untuk mencapai target penanggulangan HIV, pemangku kebijakan harus memahami dan merespons kebutuhan ODHIV dengan tepat. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan perspektif ODHIV berisiko memperparah stigma dan menghambat upaya penanggulangan HIV. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan berbasis hak asasi manusia sangat diperlukan.